“Dari Sabang hingga Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.” Lirik dari lagu ciptaan RWY Larassumbogo ini bukan sekadar penggambaran geografis, melainkan juga potret utuh keberagaman negeri ini. Di seluruh penjuru tanah air, berdiri gedung-gedung tinggi, termasuk kampus-kampus yang menjadi pusat lahirnya ilmu pengetahuan. Di dalam ruang-ruang itulah para pemuda-pemudi menimba ilmu, berdiskusi soal negara, dan memikirkan masa depan bangsa. Dari mereka pula nantinya lahir para dokter, teknisi, ekonom, guru, dan berbagai profesi yang kelak memegang peran penting dalam menjaga dan memajukan negeri ini. Siapa mereka? Tak lain adalah mahasiswa.
Secara bahasa, istilah mahasiswa terdiri dari dua unsur, “maha” yang berarti besar atau agung, dan “siswa” yang berarti pelajar. Jadi, mahasiswa merupakan pelajar tingkat lanjut yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik universitas, institut, maupun politeknik. Namun, mahasiswa sejatinya bukan hanya sekadar status akademik. Mereka kerap diidentikkan dengan julukan kaum intelektual muda, yang digadang-gadang menjadi agen perubahan (agent of change), penjaga nilai moral (moral force), sekaligus pengontrol sosial (social control). Namun idealisme ini perlahan luntur oleh rutinitas kampus, tekanan sosial, dan sikap pasif itu sendiri. Di sinilah letak ironi yang patut kita renungkan.
Mahasiswa sering dipandang sebagai sosok yang bebas berpikir, vokal terhadap ketidakadilan, dan berani melawan arus demi perubahan. Namun, banyak pula yang masih terkungkung dalam ketakutan, kenyamanan semu, dan pola pikir masa lalu. Misalnya, tak sedikit mahasiswa yang hadir di kelas hanya demi absen, bukan untuk belajar. Materi kuliah dianggap sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai ilmu yang harus dipahami. Saat dosen membuka sesi diskusi atau tanya jawab, mayoritas memilih diam dan buru-buru ingin menyudahi perkuliahan. Bukan karena tak tahu, tapi karena takut terlihat bodoh, takut ditertawakan, dan enggan menanggung risiko salah.
Lebih jauh, budaya instan pun makin mengakar. Banyak yang lebih memilih menyalin tugas dari senior atau menggunakan catatan tahun lalu, bukan karena tak mampu, tapi karena malas berpikir secara mandiri. Padahal, mahasiswa adalah mereka yang seharusnya menjadi pionir dalam membangun tradisi berpikir kritis dan logis. Tapi yang tumbuh justru budaya serba cepat, serba mudah, dan serba salin hingga akhirnya dianggap biasa saja batas kewajarannya.
Organisasi kemahasiswaan yang seharusnya menjadi ruang latihan kepemimpinan, malah tak jarang berubah menjadi wadah formalitas. Anggota hanya menjadi pengikut tanpa suara. Setiap keputusan diterima begitu saja tanpa pertimbangan atau diskusi berarti. Tak ada dinamika gagasan, tak ada perdebatan sehat dan mengakar. Yang ada hanyalah kebiasaan mengangguk dan berkata “iya”, bukan karena sepakat, tapi karena takut berbeda.
Saya pribadi pernah berada di posisi itu. Hadir di kelas hanya sebagai formalitas, datang, duduk, lalu diam. Dulu saya kira, diam adalah bentuk kehati-hatian agar tidak terlihat bodoh. Tapi semakin saya menyadari, bahwa kemampuan untuk berpikir kritis dan mengutarakan pendapat tidak muncul begitu saja. Ia harus dilatih, dibiasakan, dan dibangun melalui keberanian. Saya pernah ditertawakan saat bertanya. Pernah juga diremehkan ketika menyampaikan pendapat. Namun dari pengalaman-pengalaman itulah saya mengerti bahwa rasa malu dan takut salah adalah tembok besar bagi kemajuan berpikir kita.
Lalu pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar telah menjadi mahasiswa?. Apakah cara berpikir, bersikap, dan bertindak kita sudah mencerminkan kedewasaan intelektual?. Jangan sampai yang berubah hanya gedungnya, dari SMA ke universitas, tapi mentalitas kita masih terpaku pada pola sekolah yang hanya patuh, diam, dan menunggu perintah.
Tentu saja, ini bukan sepenuhnya salah mahasiswa. Sistem pendidikan pun memiliki andil besar. Banyak kampus masih mempertahankan budaya hierarkis yang kaku, di mana bertanya dianggap pembangkangan, dan inisiatif sering disalahartikan sebagai ancaman. Padahal, pendidikan tinggi seharusnya mendorong mahasiswa untuk tumbuh sebagai individu yang berpikir mandiri, reflektif, dan berani mengambil sikap.
Mahasiswa bukan soal usia atau status kuliah. Ini adalah soal kesadaran. Mereka yang layak disebut mahasiswa adalah mereka yang punya keberanian berpikir berbeda, menyuarakan kebenaran dengan tanggung jawab, dan mengkritisi sesuatu bukan sekadar ikut-ikutan.
by : Taufik Rohman
Referensi
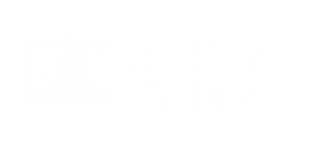





Leave a Reply